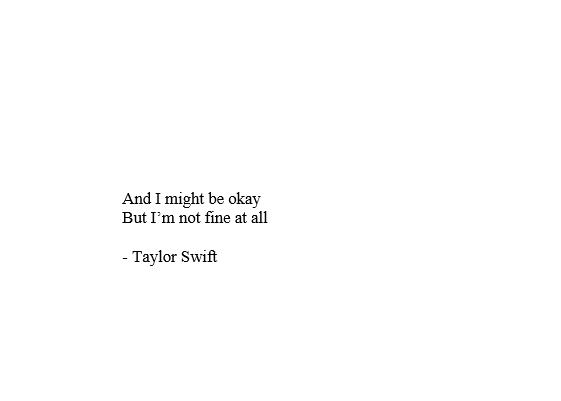“And I might be okay. But I’m not fine at all”- Taylor Swift
Aku menarik napas panjang sebelum memasuki halaman sekolah. Kalau ingat lagi semua kejadian sebelum liburan itu, sekolah sepertinya tak akan lagi menjadi tempat yang menyenangkan. Dan aku benar. Semua orang menatap aneh sewaktu aku masuk ke dalam kelas. Beberapa mata bahkan mengekor sampai aku duduk di sebelah Ei yang pagi ini menoleh pun tidak saat aku duduk di sebelahnya. Dia bergeming, tetap saja menekuni buku yang sedang dia baca, bersikap seolah aku tak ada.
Sekuat tenaga aku berusaha menahan diri untuk tak menghela napas, tak ingin dianggap mencari perhatiannya. Tapi lantas aku tak tahan untuk tak meliriknya. Hah, padahal sebenarnya aku tidak marah padanya. Seminggu ini aku malah merasa bersalah karena sudah membentak dia di muka umum seperti itu. Padahal dia sebenarnya tidak salah. Dia benar sewaktu bilang aku ini penakut. Dia benar sewaktu bilang aku tak berani memperjuangkan keinginanku. Hanya saja…
Ponsel yang ada di saku rokku bergetar. Aku segera menariknya keluar. Mas Awan. Ini lagi. Seminggu kemarin, setelah obrolan tak menyenangkan dengannya dia malam itu, Mas Awan berubah. Seminggu kemarin dia hampir tiap hari ke rumah, mengajakku pergi jika dia sedang tak ada kuliah. Bahkan futsal saja yang biasanya tak mau diganggu, mas Awan mendadak minta ditemani. Dia juga tambah sering mengirimkan pesan-pesan seperti ini, hanya sekedar mengucapkan selamat pagi, siang, atau malam, semakin sering mengecekku. Sama seperti pagi ini.
Mas Awan: udah di sekolah, Dek? Have a great day. Love you.
Aku memasukkan ponsel ke saku rok lagi tanpa membalasnya. Katanya begitu, dia tak akan menuntutku untuk selalu membalas setiap pesannya. Dia tak ingin memaksakan apa-apa.
Bel tanda pelajaran dimulai baru saja berbunyi. Lalu rasa tak menyenangkan itu bertambah lagi sewaktu aku melihat bangku di pojok depan kosong. Senja tidak masuk sekolah. Padahal aku rindu, sudah sangat ingin bertemu. Ah, bahkan setelah berhari-hari, setelah semua yang terjadi akhir-akhir ini, aku masih juga tak bisa mengeluarkan Senja dari dalam kepala, masih saja merindukannya.
Hari ini akan jadi hari yang panjang.
***
“Nggak pulang, Ta?” tanya Eko dari mejanya.
Aku memalingkan pandangan dari pintu kelas yang terus aku pandangi semenjak dilewati Ei tadi.
“Bentar, Ko. Nyelesein ini dulu,” jawabku sambil menunjuk LKS yang masih terbuka di atas meja.
“Kamu udah nengokin Senja?” tanya Eko.
Aku menggeleng. Sebenarnya ingin, tapi kalau ingat peringatan Arik lewat telpon hari itu, sepertinya akan jauh lebih baik jika aku tidak bertemu dengannya dulu.
“Aku sebenernya pengen nengokin, sih. Cuma udah terlanjur ada janji. Kemaren waktu dia opname, aku juga cuma sempet nengokin sekali.”
“Dia opname, Ko?” tanyaku kaget.
“Iya.” Eko memandang heran padaku. “Kamu nggak tau?” tanyanya.
Aku menggeleng.
“Minggu kemaren kan dia opname. Aku juga nggak sengaja taunya. Kebetulan aja dia dirawat sebelahan sama sodaraku.”
“Sakit apa dia?”
“Nggak nanya. ”
“Ogitu….”
“Kalau ke rumahnya, salam ya?” Eko kemudian berjalan cepat keluar kelas bahkan tanpa menunggu jawabanku.
Ini tak bisa lagi kutunda. Aku harus bertemu dengannya. Aku butuh bertemu dengannya. Tak peduli nanti harus seperti apa menghadapi Arik. Aku benar-benar butuh bertemu dengan Senja. Sekarang.
Buku-buku yang masih terbuka di atas meja langsung aku tutup, kubereskan bersama alat tulis yang lain, kumasukkan ke dalam tas. Dengan cepat aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas lalu mulai mengetik pesan singkat pada Mas Awan.
Me : Mas, aku pulang sama Ei, ya? Mau jalan dulu sebentar.
Tanpa menunggu balasan dari Mas Awan, aku kembali memasukkan ponsel ke dalam saku rok, menyambar jaket dari dalam laci meja, lalu melangkah cepat meninggalkan sekolah, menyeberangi jalan depan sekolah dan berbelok di pertigaan pertama di sana. Langkahku melambat saat memasuki halaman rumah Senja sebelum akhirnya kuhentikan di teras. Pintu rumah itu tertutup, tapi saat aku hampir mengetuknya, terdengar suara seseorang dari dalam.
“Terserahlah,” teriaknya.
Pintu yang ada di depanku terbuka. Ada Arik berdiri di depanku. Kami sama-sama terkejut dan saling menatap, diam mematung. Arik kemudian melipat kedua tangannya di dada, memandangku tak suka sambil menyandarkan salah satu sisi tubuhnya ke kusen pintu.
“Mau apa ke sini?” tanyanya galak.
Aku menelan ludah, tetap berusaha memasang senyum terbaikku, berusaha tak mempedulikan nada kasar dalam suaranya itu.
“Senja ada, Rik?” tanyaku.
“Senja lagi istirahat. Ada apa?” jawabnya, masih segalak sebelumnya.
Aku memaksakan senyuman. Senyuman kecewa sebenarnya karena tak bisa bertemu Senja. Tadi kupikir, aku akan bertemu dengannya, akan bisa mengurangi rasa tak menyenangkan ini. Alih-alih, aku justru harus menghadapi Arik yang tak beda dari biasanya, selalu membuat perasaanku bertambah tak menyenangkan.
“Senja sakit apa, Rik?” tanyaku.
Arik tak menjawab, hanya menatapku, masih dengan tatapan tak suka yang sama.
“Oh, ya udah kalau gitu, Rik. Salam aja.”
Aku mengulum kekecewaan. Tak apa, memang salahku juga. Aku sudah hampir meninggalkan tempat ini saat tubuh Arik sedikit ditarik, dipaksa berpindah dari tempatnya berdiri.
“Rekta?” Suara Senja menahan langkahku.
Arik langsung mendengus kesal karena Senja muncul di sebelahnya. Dia berbalik lalu berjalan masuk ke dalam rumah dan menjatuhkan diri dengan kesal ke atas sofa di depan televisi.
“Sori, Rekta,” kata Senja.
Dia benar-benar sedang sakit. Walaupun senyuman di wajahnya masih sama, tapi itu tak bisa menyembunyikan kondisinya yang sedang tak baik-baik saja. Dia sedang tak baik-baik saja.
“Kamu kok nggak istirahat?” tanyaku.
“Udah mendingan, kok.” Senja tersenyum. “Ayo masuk,” ajaknya.
Sebenarnya aku ingin masuk. Tapi tatapan sangar dari Arik yang kedua tangannya terlipat di dada, yang sekarang sedang duduk di sofa itu, membuatku urung.
“Di teras aja nggak papa kan, Ja? Aku….”
“Iya. Nggak papa.” Senja memotong ucapanku dengan cepat. Sepertinya sudah bisa membaca cuaca ruang tamu siang ini. “Ya udah. Duduk,” katanya sambil mengajakku duduk di kursi teras.
Aku mengikuti Senja, duduk di kursi kosong di sisinya.
“Kamu kok nggak bilang sih kalau sakit, Ja?” kataku. “Kamu sakit apa?”
Senja tersenyum. “Cuma lagi nggak enak badan, kok.” Dia menundukkan kepalanya, mengubur wajahnya di kedua telapak tangannya.
“Sori aku udah gangguin kamu. Aku cuma …”
Aku tak bisa melanjutkan kata-kataku. Apa yang harus kubilang? Kangen, begitu? Atau bahwa aku sangat ingin bertemu?
Senja mengangkat wajahnya dan tersenyum. “Nggak ganggu kok, Rekta. Maaf ya aku nggak kasih kabar.”
Yang kemudian ada di antara kami adalah diam. Cukup lama aku hanya diam memandanginya, tak mengatakan apa-apa. Tak bisa menemukan kata apa-apa. Ya Tuhan, aku benar-benar merindukannya.
“Rekta, are you okay?” Senja tiba-tiba memecah diam kami.
“Okay. I’m okay,” jawabku setelah tarikan napas yang lumayan panjang.
“No, you’re not.” Senja menjawab cepat. Dia menoleh ke arahku.
“Sok tau.”
“Aku memang tahu. Aku tahu kamu bertengkar sama Dewi,” katanya.
“Aku nggak papa, Ja.”
“Rekta, aku tahu kamu. Memangnya Dewi bilang apa sampai kamu semarah itu sama dia?”
Aku menghela napas lagi. Great. Setelah disambut oleh Arik seperti tadi, sekarang aku ganti diinterogasi. Dan aku tahu Senja. Aku tahu dia pasti akan mengorek semuanya, akan menasihatiku banyak sekali seperti hari itu.
“Rekta?” panggilnya.
Ya, tepat seperti ini.
“Aku ke sini cuma pengen ketemu kamu, Ja. Bisa nggak?”
“Memangnya kamu nggak pengen nyelesein masalah kamu sama Dewi?” tanyanya.
Aku membatu.
“Rekta, masalah nggak bakal selesai kalau kamu selalu lari kayak gini. Kamu rela kehilangan Dewi karena hal kayak gini?”
“Dia yang salah, Ja. Harusnya dia yang minta maaf ke aku!” Akhirnya kata-kata itu keluar juga.
“Kamu nggak bayangin posisi dia?” tanya Senja. “Kepikir nggak kalau bisa aja dia sebenernya bukan nggak mau minta maaf sama kamu? Bisa aja sebenernya dia cuma takut buat dateng dan minta maaf ke kamu?”
“Terus? Aku yang kudu minta maaf?”
“Ya kenapa nggak?” Nada suaranya tetap setenang sebelumnya. “Aku dengar kamu bentak dia di depan umum.”
“Ah udahlah, Ja.” Aku berdiri, bersiap pergi. “Harusnya aku tadi nggak usah ke sini aja. Nambahin sumpek!”
“Rekta, masalah itu ada buat diselesaiin, bukan ditinggalin. Dia nggak bakal selesai kalau kamu terus-terusan lari kayak gini.”
“Udahlah, Ja. Nggak usah sok tahu,” bentakku akhirnya.
Senja tiba-tiba berdiri, tepat di hadapanku. Dia menatapku, membuatku mendadak membatu, urung melangkah.
“Udah ya, Rekta. Udah cukup kamu nahan semua masalah kamu. Udah, jangan kamu tahan lagi.” Nadanya lembut sewaktu Senja mengatakan semua itu, berbeda dengan sebelumnya. “Aku tahu kamu capek. Jadi, udah. Jangan kamu tahan lagi. Jangan kamu tambahin lagi. Kamu selesaiin, ya? Kita selesaiin sama-sama.”
Lalu tiba-tiba cairan hangat itu menetes keluar dari kedua mataku. Air mata yang selama ini setengah mati kutahan. Masalahku dengan Ei, pertengkaranku dengan Mas Awan, tuntutan ayah, sikap dinginnya Arik yang aku masih saja tak paham alasannya… Semuanya masalah yang numpuk itu… Lalu tentang rasaku… Ah, lagi-lagi dia benar. Aku sebenarnya memang sudah lelah dengan semuanya. It’s just too much.
Aku merasakan telapak tangan Senja di pipiku. Dia tak terlihat terkejut saat air mataku membasahi tangannya. Dia pasti sudah menduganya. Lalu, entah mendapatkan keberanian dari mana, aku menjatuhkan kepalaku di dadanya dan menangis di sana. Membiarkannya membelai belakang kepalaku dengan lembut sampai akhirnya, cukup lama kemudian, aku kembali mengangkat kepala.
“Udah lebih lega sekarang?” tanyanya.
Aku mengangguk. “Iya, makasih, Ja.”
“Jadi?” tanyanya. “Kita selesaiin masalahmu sama Ei, ya?”
Kita, batinku. Kata itu terdengar menyenangkan sekali di telingaku.
“Iya. Aku bakalan selesaiin masalahku sama Ei.”
“Good.” Senja tersenyum.
Kami lantas saling diam, tak mengatakan apa pun. Aku mundur, memberi jarak di antara kami lalu berdiri bersandar pada tiang, hanya diam memandanginya, kembali tak bisa menemukan apa pun untuk dikatakan.
“Ja, makan siang dulu!” Arik muncul di pintu, menatap kesal ke arahku.
Aku melihat Senja menghela napas. “Iya, sebentar lagi,” katanya.
“Ja, ini udah lewat setengah jam. Nanti…”
“Iya, Rik. Tunggu dulu, ya? Sebentar.” Tak ada nada tinggi dalam suara Senja. Tapi aku mendengarnya berulang kali menghela napas.
Arik kembali masuk ke dalam rumah dengan kesal.
“Maaf ya, Rekta.”
“Nggak pa-pa, Ja.” Aku menegakkan tubuhku. “Ja, kalau gitu aku pulang dulu. Kamu istirahat dulu aja. Sori udah ganggu,” kataku tanpa berani mendekatinya.
“Maaf, ya?” katanya lagi.
“Iya, Ja. Nggak apa-apa. Aku yang minta maaf sudah ganggu kamu. Makasih. Oiya, ada salam dari Eko.”
Senyuman itu masih ada di wajahnya. “Iya. Makasih. Salam balik.”
“Sampaikan sendiri ya kalau udah masuk.”
Senja tersenyum, mengangguk. “Rekta?”
“Ya?”
“Aku seneng kamu datang. Makasih udah datang.”
Detak jantung ini menyakitiku sekarang. Mendengarnya mengucapkan kata itu membuat hatiku terasa semakin sakit. Apalagi ketika sebelah tangannya kembali membelai pipiku.
“Aku suka kalau kamu senyum kayak gini,” katanya saat ibu jari tangannya meraba bibirku.
Ya, aku tersenyum. Aku ingin dia tahu aku sedang tersenyum. Aku juga ingin mempertahankan tangannya tetap di sini, di wajahku. Tapi tidak. Aku tidak lagi berani melakukan itu, hanya akan menambah rasa sakit ini nanti.
“Makasih,” katanya lagi. Dia melepaskan tangannya.
“Aku pulang, Ja,” pamitku.
Senja mengangguk. “Hati-hati,” katanya, melepaskanku pergi.
Aku melangkah cepat meninggalkan rumah itu. Saat aku menoleh, Senja sudah masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Aku mengembuskan napas panjang, berusaha mengeluarkan rasa aneh yang menyelimuti hatiku semenjak tadi.
Langkahku terhenti ketika aku merogoh saku rok dan tidak menemukan kunci rumah di sana. Hanya ada ponsel saja. Aku baru sadar. Kunci rumah aku masukkan ke saku jaket tadi pagi dan sepertinya aku meninggalkan jaketku di kursi teras rumah Senja. Bodoh. Mau tak mau, aku akhirnya kembali ke rumah Senja. Ayah dan mamah sama-sama jaga siang hari ini. Jadi kalau tidak mengambil kunci itu, aku harus menunggu mereka pulang nanti malam jam sembilan untuk bisa masuk ke dalam rumah.
Aku berbalik arah, kembali ke rumah Senja. Untung pintu depan rumah itu sudah ditutup tadi. Jadi, aku cukup mengambil jaketku dan bergegas pergi.
“Rik, dia itu temenku. Tolong bersikap lebih baik sama dia.”
Suara Senja dari dalam ruang tamu itu membuatku mengurungkan langkah. Suaranya terdengar cukup keras dan kesal.
“Aku itu udah cukup baik sama dia, Ja.”
“Tadi itu apa?” tanya Senja.
“Harusnya aku yang tanya ke kamu. Tadi itu apa?” Arik balik bertanya dengan nada tinggi.
Ada jeda cukup lama. Tak ada jawaban dari Senja.
“Ja, aku kan udah bilang. Dia itu nggak serius sama kamu. Dia itu cuma jadiin kamu mainan! Buat seneng-seneng doang!”
Dadaku rasanya begitu sakit saat mendengar kata-kata Arik. Tapi dia tidak salah. Dia tidak salah menilaiku. Semua orang pasti akan menilaiku dengan cara yang sama kalau tahu apa yang sudah aku lakukan.
“Ja, aku sayang sama kamu. Aku nggak rela kalau kamu cuma dijadiin mainan sama dia. Dia itu udah punya pacar, Ja. Aku liat dengan mata kepalaku sendiri!” kata Arik lagi.
“Aku tahu.”
Aku menutup mulutku dengan sebelah tangan sewaktu mendengar jawaban Senja. Dia tahu.
“Apa?” tanya Arik.
“Aku tahu. Aku udah lama tahu soal itu.”
“Terus?”
Tidak. Aku tak bisa lagi mendengarkan semua ini. Aku berjalan cepat meninggalkan rumah Senja sambil berusaha menarik napas panjang-panjang, berusaha mengurangi rasa sakit di dadaku. Tapi, semua itu tak berguna karena rasa sakit itu masih saja ada. Manusia macam apa aku ini?
Ada getaran dari ponsel yang ada di saku rok. Dengan cepat aku mengeluarkan benda itu dari sana. Mas Awan.
“Dek, kamu di mana? Maaf tadi aku di jalan, baru buka hape.”
“Lagi jalan sama Ei. Aku pulang sendiri aja, Mas.”
“Yaudah. Kalau gitu ati-ati. I love you.”
Langkahku terhenti di pertigaan dekat sekolah. Sambungan telpon itu belum juga diakhiri, tapi tak ada lagi yang berbicara. Dari tempatnya biasa menungguku, di atas motornya, Mas Awan menatapku, masih dengan ponsel menempel di sebelah telinganya.
***
Tak ada yang berbicara sama sekali semenjak tadi. Tidak aku, tak juga Mas Awan. Tak hanya semenjak kami mulai duduk di sini, tapi semenjak kami bertemu di depan sekolah tadi. Aku masih ingat bagaimana raut wajah Mas Awan sewaktu menyambutku tadi. Aku ingat, di kedua matanya sama sekali tak ada amarah. Yang ada di sana hanya kekecewaan. Sama seperti sekarang.
Ruang tamu rumahku mendadak menjadi tempat yang tak lagi menyenangkan. Aku tak suka suasana ini. Aku tak suka rasa ini, rasa tak menyenangkan yang muncul setiap kali aku sudah mengecewakan orang dan tak tahu harus mengatakan apa. Ah, bohong. Aku tahu harus mengatakan apa. Aku tahu seharusnya aku bilang maaf ke Mas Awan. Maaf karena aku sudah berbohong padanya siang ini. Maaf karena aku sudah mengecewakan dia. Maaf karena hatiku pada akhirnya bukan buat dia. Tapi ternyata satu kata itu adalah kata tersulit yang harus aku ucapkan. Jadi pada akhirnya kami hanya duduk diam di sofa ruang tamu, membiarkan ruang ini diisi bunyi detik jam dinding sama beberapa kali mesin kendaraan yang lewat di depan rumah.
Mas Awan masih saja diam memandangiku. Aku tak tahu apa yang sedang dia pikirkan sekarang. Yang aku tahu pasti, ada kekecewaan di sana, di kedua matanya yang sedari tadi tak berhenti memandangiku. Dan itu rasanya menyakitkan.
Lama kemudian setelah sunyi, Mas Awan tiba-tiba berdiri, berjalan ke arahku lalu berlutut di lantai di hadapanku. Dia mengejar tatapan mata yang semenjak tadi aku tundukkan, yang sengaja aku hindarkan darinya, meletakkan telapak tangannya di kedua pipiku.
“Dek,” panggilnya.
Dengan terpaksa aku memandangnya. Masih tak bisa mengatakan apa-apa, hanya memandanginya.
“Maaf,” ucapnya.
Air mataku langsung jatuh. Mas Awan… Senja… Mereka semua orang baik. Tapi apa yang sudah aku lakukan pada mereka? Aku hanya bisa mengecewakan mereka, menyakiti mereka. Aku ini manusia macam apa?
“Mas..” Suaraku tercekat. Tapi bahkan sebelum aku berusaha untuk meneruskan kata-kataku, Mas Awan sudah berhasil menyuruhku diam lagi.
“Maafin aku, ya?” katanya. Dia menghapusi air mata yang tak lagi bisa kutahan. “Aku selama ini nggak bisa jadi cowok yang baik buat kamu. Aku nggak bisa pahami kamu. Maafin aku ya, Dek?”
Aku semakin terisak. Mengapa malah seperti ini? Mengapa dia yang mengatakan maaf? Bukan dia yang salah. Aku yang salah. Aku yang seharusnya minta maaf.
“Dek, kita mulai lagi semuanya dari awal, ya? Aku bakal belajar lebih ngertiin kamu.”
“Mas.. aku…”
“Please jangan bilang itu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku sayang banget sama kamu.”
Aku menarik napas panjang, meletakkan tanganku di atas tangannya yang masih saja ada di kedua pipiku. Aku menarik lepas tangannya lalu menatap kedua matanya. Tidak. Aku tidak bisa menyakitinya lagi. Tak bisa. Tak boleh.
“Kita mulai lagi dari awal, ya?” Mas Awan bertanya sekali lagi dan kali ini aku menganggukkan kepala.
Bersambung